Oleh : IGNAS KLEDEN
Nama Sardono W. Kusumo telah masuk dalam kosakata nasional dan internasional seni pertunjukan, khususnya tari, semenjak 1970-an. Namun demikian, belum banyak kiranya yang tahu bahwa tokoh ini adalah juga seorang penulis yang patut diperhitungkan. Esai-esainya yang dibahas di sini menunjukkan bahwa dia bukan saja seorang pencipta seni tari yang subur, melainkan juga seorang yang tekun dan telaten memikirkan apa yang sedang dikerjakannya.
Perlu segera ditambahkan bahwa pemikiran yang tertuang dalam esai-esai ini bukan sekadar hasil studi kepustakaan yang tekun, tetapi merupakan percikan dari pergulatannya yang relatif total dengan apa yang dikerjakannya. Yaitu, meneliti dan terlibat di lapangan penelitian, berpartisipasi secara intens dalam suatu komunitas yang hendak diamati dan diakrabinya, membandingkan alam fisik dan representasinya dalam susunan organisasi sosial serta pandangan hidup suatu kelompok sosial, dan, tidak kurang dari itu, mengajukan dugaan-dugaan yang berani semacam bold conjectures dalam pengertian Karl R. Popper tentang apa yang sedang dipelajari dan dicoba dihayatinya.
Mungkin di antara seniman-seniman Indonesia dia adalah salah seorang di antara beberapa yang dengan tegas mengatakan bahwa kesenian bukanlah sekadar memberi hasil, produk, prestasi dan output, tetapi sekaligus juga suatu prosedur, pendekatan dan bahkan metode. Dalam praktik, ini artinya Sardono belajar tentang tari kecak di Desa Teges, Kelurahan Gianyar, Bali, bukan hanya untuk dapat menarikan tari kecak dengan benar, tetapi berarti juga mencoba mengenal berbagai persyaratan sosial-budaya dan sosial-ekonomis, dan bahkan prasyarat demografis yang mendorong kelahiran dan diterimanya tari kecak dalam komunitas pendukungnya.
Desa Teges relatif kecil, dengan penduduk tidak lebih dari 77 kepala keluarga (KK). Hanya terdapat satu jalan besar sepanjang 400 meter yang membelah desa itu. Semua penduduk berasal dari satu kasta yang sama, dan mengalami suatu kehidupan yang sangat jauh dari kota. Dengan demikian, mereka harus mengembangkan suatu cara hidup bersama dalam lingkungan sempit yang tidak memberi kemungkinan untuk banyak pilihan lain. Cara itu ialah mengorganisasikan bentuk kebersamaan yang solid, yang ditunjang oleh kesediaan berbagi. Adapun kesediaan berbagi ini dimaksudkan agar tiap orang dalam komunitas tersebut mendapatkan sesuatu dan sekaligus juga menyumbangkan sesuatu. Dalam rumusan yang lebih teknis: yang diusahakan bukan saja pemerataan hasil-hasil yang diperoleh (atau equal results) tetapi juga pemerataan kesempatan berusaha (atau equal opportunities).
Dalam deskripsi Sardono hal ini diungkapkan dengan serba-ilustratif. Para penari kecak di Teges mempunyai kebiasaan mempertimbangkan kemampuan teman menarinya selagi mereka menari bersama. Jadi, seorang penari akan mengukur dengan cermat seberapa jauh dia dapat mengerahkan dan menunjukkan kemampuannya agar memancing dan merangsang kemampuan dan kegairahan sesama penari, dan seberapa jauh pula dia harus mengekang diri dan kemampuannya, agar tidak melumpuhkan daya kreatif mereka, karena merasa tak berdaya mengimbangi seseorang dengan kemampuan yang tak tergapai oleh mereka.
Rupanya dengan alasan yang sama pemahat Lempad sengaja membiarkan di rumahnya beberapa patung yang tak selesai, agar anak cucunya dapat mempunyai sesuatu untuk diselesaikan di kelak kemudian hari (Sardono: 109). Menurut Sardono kebiasaan ini tidak hanya terdapat di kalangan seniman Bali, tetapi juga menjadi kebiasaan para penari Malulo di Sulawesi atau penari Seudati di Aceh.
Dengan demikian, kesenian pada awalnya mengikuti Sardono-tidaklah dipahami dan dihayati sebagai the pursuit of excellence individual, saat seorang seniman menunjukkan semua kemampuan kreatif yang ada pada dirinya, melainkan ikhtiar bersama untuk memancing dan menghidupkan daya kreatif dan energi hidup dalam diri setiap orang, sehingga potensi-potensi itu dapat menolong dia dalam menghadapi berbagai situasi sulit dalam hidupnya. Seni bukanlah sekadar keasyikan pribadi dengan yang indah, melainkan semacam latihan dan sekolah untuk orang yang terlibat di dalamnya agar terampil dan terlatih mengerahkan energi kreatifnya untuk menghadapi setiap masalah. Maka, tari kecak di Desa Teges, Bali, tarian perang di Nias, atau tarian orang Dani di Papua, bukanlah sekadar pameran atau pementasan, tetapi tempat dan saat masing-masing orang memberi sesuatu dan mengambil sesuatu, mengajar sesuatu dan belajar sesuatu dari orang lain. Dalam berbagai komunitas, seni pertunjukan bukanlah show room tetapi lebih mirip workshop ketika orang-orang yang terlibat di dalamnya saling melakukan tukar-menukar potensi dan saling menguji energi kreatifnya.
Tak perlu diterangkan panjang lebar bahwa disiplin latihan dalam kesenian tiap komunitas dapat berbeda satu dari yang lainnya. Perbedaan ini tergantung pada pandangan hidup dan pandangan tentang peran dan kedudukan seni dalam kebudayaan dan kehidupan sosial suatu komunitas. Perbandingan yang dibuat Sardono antara tari kecak di Bali dan latihan dalam dunia pewayangan di Jawa (Sardono: 74) dapat memperjelas hal ini.
Dalam wayang karakter-karakter yang diperankan dihayati sebagai jiwa ideal yang harus dicontoh dan dituju. Persiapan untuk memainkan atau memerankan Arjuna direalisasikan dalam puasa dan mortificatio, yaitu pengekangan diri secara keras seakan seseorang melaksanakan mati dalam hidupnya. Sedangkan untuk menarikan Gatotkaca atau Hanuman, dibutuhkan latihan dan keterampilan tinggi dalam pencak silat. Sebaliknya dari itu, di desa Teges, Bali, persiapan menari didahului oleh rapat-rapat desa yang melibatkan semua pihak: pendeta, guru tari, dan kepala desa. Sebuah tontonan atau pertunjukan seni senantiasa berhubung dengan kerukunan sosial dan melibatkan syarat-syarat keagamaan.
Kalau di Teges suatu pertunjukan seni selalu didahului oleh rapat desa, maka di Nias rapat desa yang dalam bahasa setempat dinamakan orabua-menjadi saat dan tempat orang-orang memperlihatkan bakat-bakatnya dalam sastra dan teater (Sardono: 106). Rapat itu dihadiri oleh lelaki dan perempuan, anak-anak, orang dewasa dan orang tua, yang semuanya mendapat kesempatan berbicara. Perdebatan antara peserta rapat dipandu oleh seorang yang berperan sebagai moderator. Pembicaraan dalam rapat tidak dilakukan secara lugas, tetapi dibumbui berbagai dongeng dan peribahasa serta tamsil-ibarat, yang disampaikan dalam retorika yang teatral. Maka rapat desa itu terlihat bagaikan suatu seni pertunjukan sendiri dengan suasana spiritual yang kuat.
Beberapa contoh di atas yang diajukan oleh Sardono dari pengalaman lapangannya semakin mempertegas pandangannya, bahwa seni pertunjukan dan seni pada umumnya patutlah dilihat dalam perspektif makro sebagai sebuah jendela atau kisi-kisi untuk memandang kebudayaan dan meninjau kehidupan sosial suatu komunitas yang mendukung kesenian tersebut. Kesenian adalah sebuah kode untuk membaca teks kebudayaan. Pada titik itu Sardono dengan sekali gebrak telah menghapus garis pemisah yang ditarik secara artifisial di antara pandangan ilmiah (berupa studi-studi ilmu sosial dan studi-studi humaniora tentang kesenian) dan dan kajian artistik dan estetika tentang kesenian.
Studi ilmu-ilmu sosial dapat membawa kita kepada pemahaman bahwa kesenian hanyalah suatu fungsi sosial yang berperan menjaga dan memperkukuh integrasi sosial. Dalam hal ini fungsi kesenian dianggap tak berbeda dengan fungsi ritual misalnya. Sebaliknya dari pandangan itu, kesenian dapat juga dilihat sebagai locus tempat konflik-konflik politik, pertentangan antar-etnik atau ketegangan ekonomi dipertunjukkan dan direpresentasikan.
Studi-studi humaniora tentang kesenian jelas sangat dekat dengan kajian estetika dan tinjauan artistik tentang kesenian, karena tiap ekspresi seni dipandang sebagai usaha seseorang untuk menerjemahkan potensi dan bakat-bakatnya menjadi suatu kenyataan dalam tindakan dan perwujudan dalam benda-benda fisik. Atau, kesenian dilihat sebagai hasil pertemuan seseorang dengan lingkungan hidup atau lingkungan budaya tertentu. Tulisan Bakdi Soemanto tentang pertumbuhan dan perkembangan Rendra sebagai seorang pribadi seniman dapat dijadikan contoh soal tentang pendekatan humaniora dalam kesenian. Selanjutnya tulisan Rendra tentang dua orang penari, Ibu Dewi (70 tahun) dan Ibu Sawitri (60 tahun) dari Kecamatan Losari di timur Cirebon adalah contoh pendekatan artistik dan estetika terhadap seni.
Tulisan-tulisan Sardono secara intuitif merupakan gabungan yang spontan dari berbagai pendekatan tersebut. Dengan persepsi yang cepat dia memahami mengapa orang Dayak Kenyah selalu berdiri dalam posisi kaki setengah berjinjit, karena dengan posisi yang demikian mereka selalu siap berlari, berjalan cepat atau melompat dalam hutan. Demikian pun gerak tangan orang Dani di Papua yang cenderung menyilang di dada hingga menyentuh pundak, adalah sebuah gerakan dominan dalam tarian mereka, yang sekaligus merupakan spontanitas motorik tangan melindungi badan dari hawa dingin dataran tinggi tempat mereka tinggal. Atau, watak orang-orang Asmat yang menyimpan keruwetan dalam penampilan yang tenang dijelaskannya dengan merujuk ke sungai-sungai yang mengalir tenang di sekitar mereka, lalu menjelma menjadi sungai-sungai kecil yang saling memotong dan menciptakan labirin yang kompleks. Ke sanalah orang-orang Asmat memancing musuhnya untuk bertempur (Sardono: 47). Tidaklah mengherankan bahwa beberapa peneliti asing yang membaca buku Sardono mengira dia seorang peneliti antropologi.
Namun demikian, antropolog atau bukan, esai-esai Sardono memberi wawasan kepada pembaca bahwa kesenian pada dasarnya bukanlah suatu bidang kegiatan yang serba-esoterik, tetapi berhubungan langsung dengan kegiatan-kegiatan lain, dan berkembang karena bersentuhan dan berinteraksi dengan sektor-sektor lain. Almarhum I Nyoman Pugra adalah seorang penari Bali dari desa Kasiman, yang turut menari dalam Dongeng dari Dirah dan ikut berkeliling Eropa selama 4 bulan. Menjawab pertanyaan Sardono tentang syarat-syarat menjadi penari yang baik, dia berkata: “Seorang penari yang baik ialah penari yang tahu menabuh gamelan, tahu membikin pakaian dan topeng, dan tahu tentang kesusastraan. Tapi lebih baik lagi kalau dia juga tau agama yang tumbuh di lingkungan dan tahu adat-istiadat masyarakatnya”. Namun demikian, “yang terbaik kalau dia sekadar petani biasa” (Sardono: 45). Ucapan petani desa ini jelas menunjukkan keyakinan bahwa kesenian tidak bisa dipelajari hanya sebagai suatu spesialisasi, karena mengandaikan pengertian tentang berbagai bidang kehidupan lainnya sebagai sumber bagi sensitivitas dan vitalitas yang menghidupkan kesenian tersebut.
Ini juga barangkali sebabnya Sardono berkeyakinan bahwa panggung untuk suatu seni pertunjukan bukanlah sekadar stage yaitu ruang berukuran sekian meter panjang dikali sekian meter lebar, melainkan masyarakat dan kebudayaan pendukung dan penikmat kesenian tersebut. Dengan demikian tugas seorang seniman pertunjukan bukanlah sekadar mengisi ruang secara fisik, melainkan mengisi sesuatu ke dalam kebudayaan. Tentulah hal ini terdengar bagaikan tuntutan yang tinggi dan abstrak, tetapi menjadi perkara yang serba- konkret dan praktis untuk seorang seniman seperti Sardono.
Suatu hari di Bali Sardono menari di hadapan beberapa penari Bali. Seorang penari rupanya memerlukan perlengkapan untuk menari menanggapi tarian Sardono. Kebetulan yang ada di sekitar situ hanyalah tali plastik. Maka menarilah penari tersebut dengan menggunakan tali plastik sebagai perlengkapannya, suatu hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dalam arti itu bukan saja masyarakat dan kebudayaan yang dapat menjadi panggung besar tetapi juga segala sesuatu yang ada dalam suatu lingkungan sosial dapat menjadi perlengkapan, setting, dan bahkan dekor pertunjukan.
Maka tidaklah mengherankan bahwa Sardono memahami dengan penuh simpati mengapa suku-suku Dayak selalu berpindah-pindah tempat setelah beberapa tahun. Pertama, tanah tempat tinggal mereka mempunyai humus tipis yang segera habis setelah ditanami satu-dua tahun. Kedua, bagi orang Dayak seluruh kawasan hutan adalah ibarat pekarangan rumah tempat mereka dapat bergerak leluasa tanpa merasa terasing.
Karena itulah perusahaan-perusahaan besar yang kemudian mematok batas-batas yang tak boleh dilanggar, merupakan suatu kejutan budaya dan pukulan kejiwaan seperti halnya melarang yang empunya rumah berjalan di pekarangan rumahnya sendiri. Dunia suku-suku Dayak bukanlah suatu dunia sedentair tempat orang menanam akar kehidupan dan tradisinya di suatu tempat, melainkan dunia para pejalan yang menjelajah hutan tahun demi tahun, untuk memberi kesempatan tanah yang telah diolah memulihkan humusnya, sambil mencari daerah baru yang memberi humus baru, kehidupan baru dan harapan baru.
BAB DUA
Sardono, dengan cara itu, memasuki kesenian berbagai suku di Indonesia bagaikan masuk dan tinggal dalam rumah para anggota komunitas-komunitas tersebut untuk menghayati bagaimana pandangan dunia mereka diterjemahkan dalam pembagian ruang dan pola arsitektur mereka. Pembagian ruang kemudian menjadi petunjuk bagaimana sekelompok orang melihat dunia mereka dalam dimensi spasial dan bagaimana dimensi ini berhubungan dengan kemerdekaan mereka bergerak atau disiplin mereka untuk diam dan mengambil tempat dalam struktur. Maka pengertian dan penghayatan seni sebagai “ruang dalam” kebudayaan dapat membuat orang memahami kebudayaan dalam keseluruhannya.
Inilah barangkali sebabnya mengapa perhatian Sardono tertarik pada apa yang dinamakannya kebudayaan non-materil. Sekalipun istilah ini tidak dijelaskannya dalam suatu konseptualisasi yang lebih rinci, maknanya mudah dipahami dengan melihat apa yang dilakukannya. Yang dia maksudkan kira-kira sama dengan apa yang och para ahli dinamakan sistem pengetahuan dan sistem nilai kebudayaan. Pengetahuan memberi orang cara untuk menghadapi dunia dengan orientasi yang tepat, yaitu yang memungkinkan sekelompok orang hidup di dalamnya dan menemukan makna dari partisipasi mereka dalam dunia itu. Seterusnya, sistem nilai memberikan pedoman mengenai apa yang patut dilakukan, dapat dilakukan, atau tak boleh dilakukan dengan dunianya itu. Mengikuti sarjana antropologi Clifford Geertz, pengetahuan dalam kebudayaan membentuk pandangan dunia (world view), sedangkann sistem nilai akan membentuk etos dalam kebudayaan. Hubungan di antara keduanya amatlah eratnya, karena pandangan dunia mengubah suatu nilai menjadi pengetahuan, sedangkan etos mengubah pengetahuan menjadi nilai.
Yang satu menunjukkan apa yang patut diketahui tentang dunia, sementara yang lainnya menunjuk kepada apa yang harus dilakukan terhadap dunia itu.
Dalam pandangan orang Dayak Kenyah, misalnya, hutan adalah tempat mereka mendapatkan kehidupan. Pohon-pohon hanya ditebang kalau mereka hendak membuka ladang atau tegalan atau kalau mereka hendak membangun rumah panjang (lamin). Di luar keperluan tersebut tidak terbayangkan bahwa orang-orang akan menebang atau merobohkan pohon-pohonan. Maka dapatlah dibayangkan betapa terguncangnya mereka tatkala perusahaan-perusahaan besar datang dengan mesin modern, merobohkan pohon-pohon besar dengan usia yang sudah purba, menyeret batangnya ke sungai tanpa terlihat maksud apa pun untuk membuka ladang baru atau tegalan baru.
Keguncangan itu bertambah hebat tatkala para pemegang HPH mulai mematok batas dan melarang penduduk setempat memasukinya untuk memburu seekor babi atau rusa, atau menguber beberapa ekor burung. Dalam peristiwa itu baik pandangan dunia penduduk setempat mau pun etos yang mereka pegang teguh selama berabad-abad roboh ditebas oleh gergaji mesin. Hutan ternyata bukanlah tempat kehidupan tetapi kawasan yang boleh diacak-acak, sedangkan ratusan pohon boleh ditebang sementara batang-batangnya yang besar dan kukuh diseret ke sungai tanpa orang bermaksud membuka ladang dan tegalan atau membangun rumah panjang.
Dalam pandangan Sardono kebudayaan non-materil inilah dalam bentuk sistem pengetahuan dan sistem nilai-yang harus dijaga pada setiap kelompok sosial, karena dua perkara inilah yang memberi daya hidup dan membangkitkan potensi kreatif dalam kebudayaan dan kehidupan suatu komunitas. Pandangan atau keyakinan ini pada hemat saya membawa sekurang-kurangnya dua konsekuensi.
Pertama, dalam interaksi antarbudaya hal terpenting yang harus dipelajari adalah sistem pengetahuan dan sistem nilai ini. Dalam arti itu hampir tak banyak manfaatnya mengambil alih teknologi dalam wujud benda-benda fisik tanpa mengambil alih rasionalitas teknologi tersebut. Mengambil alih komputer tentu banyak gunanya, tetapi tanpa mengambil alih rasionalitas komputer, produktivitas kerja tidak dengan sendirinya meningkat. Demikian pun menggunakan email barulah ada artinya kalau orang menyesuaikan diri dengan tempo yang dituntut oleh email. Kalau sebuah email dibalas setelah lima hari misalnya, maka orang tersebut masih hidup dengan tempo air mail dan bukannya dengan tempo email.
Kedua, dalam pertemuan dua kebudayaan atau dalam perubahan budaya secara umum, perlu sekali dijaga agar kebudayaan non-materil masing-masing pihak tidak dihancurkan oleh pertemuan budaya tersebut. Sebabnya, guncangnya pandangan dunia akan sekaligus mengganggu etos dan kepercayaan diri para pendukung kebudayaan tersebut, yang membuat mereka merasa tak berdaya. Pada pertengahan 1970-an sebuah desa terpencil, Bawamataluo, di Pulau Nias, mulai dibuka untuk para wisatawan. Kemudian turunlah 200-an turis kulit putih dari kapal “Prisendam” mengunjungi desa itu. Selama dua jam penduduk desa mempertunjukkan berbagai kepandaiannya, khususnya kepandaian melompati batu setinggi dua meter. Sebaliknya, para turis memamerkan berbagai perlengkapan modern: alat foto, alat perekam suara, baju aneka warna dan bentuk, dan tentu saja uang.
Sekonyong-konyong terjadilah loncatan besar dari peradaban zaman batu ke peradaban zaman plastik. Semuanya berlangsung intens hanya dalam dua jam. Akibatnya, setelah pengalaman pendek ini orang-orang Nias di desa tersebut seakan mengalami suatu kehilangan besar, yaitu hilangnya kepercayaan diri mereka. Turis-turis itu memamerkan berbagai produk yang masuk bersama kedatangan mereka, yang kemudian segera hilang kembali bersama kepergian mereka. Apalagi dengan uangnya para turis tersebut telah membawa pergi barang-barang yang menjadi tanda identitas penduduk setempat dalam kebudayaan, seperti harta pusaka dan barang-barang antik yang telah menemani mereka untuk waktu sekian lama dan menjadi mata-rantai yang menghubungkan mereka dengan sejarah komunitas mereka.
Apa yang terjadi antara orang Dayak Kenyah dan para pengusaha kayu pemegang HPH terjadi juga antara para turis kulit putih dan orang desa di Pulau Nias. Pertemuan budaya itu secara sinkronis memutuskan hubungan mereka dengan dunia dan secara diakronis memutuskan hubungan mereka dengan sejarahnya. Pembaharuan dan perubahan budaya dapat mempunyai efek yang konstruktif atau destruktif tergantung dari apakah pengaruh budaya baru memperkuat apa yang sudah ada dalam suatu kebudayaan atau justru memperlemah dan menghancurkannya. Ini artinya, kalau perubahan budaya yang terjadi masih menjamin kontinuitas dengan situasi kebudayaan sebelumnya, maka semakin konstruktif efeknya. Sebaliknya, diskontinuitas dengan masa lampau cenderung menimbulkan disorientasi (karena terganggunya pandangan dunia) dan demoralisasi (karena terganggungnya etos dalam kebudayaan tersebut).
Percobaan yang dilakukan oleh Sardono bersama dengan para mahasiswa LPKJ (yang sekarang bernama IKJ) adalah mendatangi kelompok-kelompok budaya di berbagai daerah, membuat mereka semakin menyadari potensi budaya mereka sendiri dan memperkuat potensi tersebut. Yang dicoba adalah apa yang oleh Sardono dinamakan dialog seni dengan penduduk setempat. Selama dua bulan di Nias mahasiswa tari LPKJ mencoba memperkuat kesadaran penduduk setempat bahwa menari adalah kegiatan yang punya kepentingan dan makna yang lebih besar daripada sekadar menghibur para turis. Penari setempat diajak dan dilatih mempertajam naluri-naluri mereka untuk semakin peka menangkap nilai-nilai yang ada dalam tradisi.
Demikianlah kostum tari yang dibuat dari kulit kayu sudah mulai dilupakan orang. Tetapi mahasiswa tari LPKJ ingin mencoba mengenakannya. Maka berangkatlah orang-orang ke hutan mencari kulit kayu yang kemudian dikenakan oleh mahasiswa Jakarta ini untuk menari. Percobaan itu menghidupkan kembali gairah di kalangan orang muda setempat, yang perlahan-lahan mengapresiasi kembali tradisi mereka, dan menghayati tarian sebagai aktivitas kebudayaan yang memperkaya diri mereka sendiri, dan bukan sekadar hiburan buat para wisatawan yang kebetulan mampir. Atas cara yang sama mahasiswa musik mencoba mempelajari musik Nias, sambil membantu penduduk memahami pengaruh musik diatonis dalam lagu-lagu tradisional mereka.
Eksperimen ini menunjuk beberapa pengalaman yang amat penting untuk perkembangan budaya. Berkesenian ternyata bukan hanya pekerjaan menunggu ilham, melainkan mencari ilham dengan mempelajari dan memburunya ke mana-mana, seperti para pencari emas yang bertualang ke daerah-daerah baru dan menggali tambang untuk menemukan harta karun tersebut. Kesenian bukan saja proses belajar, tetapi juga suatu kepandaian yang hanya dapat diraih melalui studi dan penelitian serta keterlibatan yang intens. Pada titik inilah dapat dilihat perbedaan di antara penelitian seni sebagai pekerjaan murni-ilmiah dengan penelitian seni sebagai persiapan untuk kerja kreatif.
Tugas penelitian ilmiah adalah mendokumentasikan, mendeskripsikan, menguraikan dan menafsirkan kebudayaan untuk memahami dan menjelaskannya. Penelitian seorang seniman, untuk meminjam kata-kata filosof Hans-Georg Gadamer bukan saja berhenti pada subtilitas intelligendi (yaitu memahami ekspresi budaya sebagai suatu Gestalt atau keseluruhan), bukan juga subtilitas explicandi (menguraikan bagian-bagian suatu keseluruhan menjadi detail), tetapi terutama menekankan subtilitas applicandi (yaitu menerapkan pengertian kita pada suatu situasi baru). Tahap ini merupakan ujian tertinggi bagi pemahaman, karena hanya dalam praktik akan diketahui apakah pemahaman kita benar atau keliru.
Mempelajari bahasa dapat menjadi ilustrasi yang baik. Kamus memang menjelaskan arti setiap kata. Namun demikian, barulah kalau seseorang menggunakan kata-kata tersebut dalam kalimat untuk suatu konteks konkret, bisa diketahui apakah penggunaan kata-kata tersebut menunjukkan pemahaman yang tepat atau melenceng. Maka penelitian seni oleh seorang seniman adalah contoh soal bagi tesis Gadamer: Verstehen ist anwenden (memahami adalah menerapkan).
Tampak dari eksperimen ini, kesenian bukanlah suatu kegiatan yang berada di luar kehidupan sehari-hari melainkan menjadi bagian darinya. Seniman bukanlah makhluk yang sangat khusus tetapi hanya manusia biasa seperti petani atau nelayan, yang mewujudkan energi kehidupan dan potensi kreatifnya dalam bidangnya masing-masing. Penari yang baik hendaknya tahu tentang sastra dan agama, tahu adat-istiadat, tahu pula menabuh gamelan dan membuat topeng serta pakaian, tetapi paling baik kalau penari adalah petani biasa saja begitu kata penari I Nyoman Pugra dari desa Kasiman, Bali Ketika penari ini meninggal selagi menari di Keraton Solo, anaknya tampil menyelesaikan tariannya, persis seperti keadaan seorang anak petani, yang meneruskan pekerjaan ayahnya di ladang, setelah ayah ini meninggal dunia.
BAB TIGA
Dilihat dari segi penelitian sosial, apa yang dilakukan oleh Sardono merupakan contoh yang menarik untuk jenis penelitian yang dinamakan participatory action research atau yang disingkat sebagai PAR. Penelitian jenis ini mencoba memberikan variasi terhadap penelitian sosial empiris yang biasa, dengan menekankan sekurang-kurangnya tiga hal berikut ini.
Pertama, pembedaan dan bahkan jarak yang sering dibuat antara peneliti dan kelompok sosial yang ditelitinya, dicoba dihilangkan. Caranya adalah dengan memperlakukan kelompok yang diteliti bukan saja sebagai objek yang diteliti tetapi sebagai sesama pelaku dalam penelitian. Beberapa antropolog bahkan lebih menegaskan hal ini dengan mengatakan bahwa perbedaan antara seorang etnograf dan seorang informan yang dianut dalam etnografi klasik adalah perbedaan yang semu. Sebab, baik kelompok yang diteliti maupun sang antropolog yang meneliti sama-sama berfungsi sebagai informan satu terhadap yang lainnya. Hal ini berlaku terutama kalau penelitian dilakukan terhadap kelompok-kelompok sosial yang anggota-anggotanya sudah banyak yang terpelajar.
Kedua, hasil-hasil penelitian harus terbuka, dan diketahui serta dapat dimanfaatkan oleh kelompok yang diteliti. Pihak yang diteliti bukan saja menjadi sumber informasi (informan), melainkan seyogyanya menjadi pihak pertama yang mempunyai akses kepada informasi yang dikumpulkan, dan dapat memanfaatkan informasi tersebut. Hal ini masuk akal, karena semenjak awal mereka tidak diperlakukan hanya sebagai sumber informasi, tetapi juga sebagai sesama peneliti yang bekerja sama dengan peneliti yang datang dari luar kelompok mereka. Kedua pihak saling memberikan informasi satu sama lain, dan karena itu kedua pihak tersebut sama-sama berhak memanfaatkan informasi yang telah mereka hasilkan secara bersama-sama pula. Ini sangat berlainan dengan penelitian sosial empiris atau etnografi klasik, di mana kelompok yang diteliti tidak pernah tahu-menahu tentang apa yang dikatakan atau ditulis tentang diri mereka, sementara informasi tentang diri mereka ini diterbitkan di London, Amsterdam, Tokyo atau Massachusetts dan menjadi bahan perdebatan dalam konferensi-konferensi ilmiah internasional yang tidak ada kena-mengenanya dengan diri dan nasib mereka sehari-hari.
Ketiga, dalam penelitian sosial empiris, tujuan akhir penelitian adalah mendapatkan dan menguji informasi ilmiah yang diperoleh untuk memperbesar dan memperluas serta menyempurnakan khasanah pengetahuan ilmiah yang ada. Jadi yang menjadi tujuan seluruh kerja penelitian adalah sumbangan atau kritik terhadap the body of knowledge yang sudah ada dalam suatu disiplin ilmiah. Di sini, kelompok sosial yang diteliti benar-benar berfungsi sebagai lapangan penelitian (research field) tempat informasi-informasi antropologis dan sosiologis dikumpulkan-kira-kira sama halnya dengan hutan-hutan di Kalimantan yang menjadi lapangan penelitian untuk jenis-jenis anggrek bagi seorang botanikus.
PAR membalikkan kebiasaan ini dengan menekankan bahwa tujuan penelitian bukanlah sekadar mengumpulkan informasi dan pendapat tentang suatu kelompok sosial, melainkan, berdasarkan informasi tersebut, menciptakan saling pengertian yang semakin mendalam dengan kelompok yang diteliti. Seterusnya saling pengertian ini menjadi landasan bagi solidaritas dan kerja sama di antara peneliti dan kelompok yang ditelitinya, yang direalisasikan dalam aksi bersama untuk memperbaiki nasib dan kondisi hidup mereka. Tentu saja dapat muncul pertanyaan di sini: apakah tujuan aksi ini tidak merugikan sifat ilmiah dari pengetahuan yang dikumpulkan, karena misalnya aksi bersama dianggap lebih penting dari validitas informasi yang diperoleh.
Adapun pertanyaan kritis tersebut mengandaikan adanya pertentangan atau perbedaan kepentingan di antara validitas pengetahuan ilmiah dan manfaat serta keberhasilan suatu aksi dan kegiatan untuk memperbaiki kondisi hidup. Pertentangan tersebut sebetulnya tidak ada, karena suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi hidup hanya berguna dan mencapai tujuannya, apabila tindakan tersebut didasarkan pada informasi yang valid tentang keadaan yang ada. Informasi yang keliru akan menghasilkan langkah perbaikan yang keliru dan melenceng dari tujuan perbaikan, semata-mata karena landasannya ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini justru menjadi amat penting pada komunitas-komunitas tradisional yang masih menganut pandangan dunia yang seringkali amat berbeda dari pandangan dunia para peneliti yang biasanya datang dari daerah perkotaan.
Dalam kesenian Bali hal ini sadar tak sadar telah berlangsung antara 1920-an hingga 1940-an tatkala beberapa seniman Barat datang ke Bali dan berdialog dengan seniman-seniman setempat dalam suatu proses saling belajar dan saling mengajar yang intens, yang akibatnya kemudian terlihat dalam perkembangan kesenian Bali. Beberapa nama yang sudah dikenal luas dan disebut kembali oleh Sardono dengan penuh penghargaan adalah Collin Macphy yang mempelajari gamelan dan menyekolahkan I Made Grindem, yang kemudian menjadi seniman penting di Desa Teges, Rudolf Bonnet dan Arie Smit yang melatih pelukis-pelukis muda Bali, Katherine Mesershon, Walter Spies dan kemudian disusul oleh antropolog-antropolog kenamaan seperti Gregory Bateson dan Margareth Mead. Sayang bahwa tidak banyak komunitas seniman di Indonesia mengalami nasib baik sebagaimana yang dialami oleh seniman-seniman Bali pada tahun-tahun sebelum Indonesia merdeka.
Sadar tak sadar, sengaja atau kebetulan, hal yang sama telah dilakukan oleh Sardono dan para mahasiswa LPKJ pada dasawarsa 1970-an hingga 1980-*an. Mereka mendatangi komunitas-komunitas budaya di Nias, Kapo Ayan di Kalimantan, Toraja di Sulawesi Selatan, suku Asmat dan Dani di Papua, hingga ke Desa Teges di Bali. Uniknya, komunitas-komunitas ini bukan saja menjadi daerah penelitian, tetapi menjadi tempat mereka melakukan talent scouting, yaitu menemukan bakat-bakat seni di kalangan penduduk setempat dan melibatkan mereka dalam proses saling belajar dan saling mengajar yang intens, dan pada tahap selanjutnya mengikutsertakan mereka dalam performance kasenian ini, nasional maupun internasional. Begitulah, penari-penari desa Teges, Bali, dibawanya ke Nancy, Perancis, ke Roma dan ke Tokyo untuk menari di pusat-pusat kesenian di sana. Demikian pun ketika Desa Tanjungmanis di Kalimantan Timur hangus terbakar dalam bencana api yang menelan 3,5 juta hektar hutan, Sardono dan mahasiswanya mengerahkan sumbangan bibit cengkeh, lada dan vanili, dan membawa tiga mahasiswa ke Bogor untuk belajar menanam dan memeliharanya.
Terlihat di sini adanya suatu solidaritas yang hidup dan kuat di antara para peneliti LPKJ dan komunitas-komunitas budaya yang mereka datangi. Informasi dan wawasan-wawasan baru yang mereka peroleh selama berada di tengah komunitas-komunitas tersebut tidak hanya disusun rapi dan dibawa pulang ke LPKJ, melainkan langsung dimanfaatkan bersama komunitas setempat, yang juga dilibatkan secara aktif dalam berbagai eksperimen kesenian yang mereka lakukan.
Contoh-contoh ini semakin memperjelas bagaimana penelitian kesenian untuk tujuan kreatif seyogyanya dilakukan. Untuk mengutip Hans-Georg Gadamer sekali lagi, penelitian sosial empiris tentang kesenian cenderung hanya berhenti pada subtilitas intelligendi (pemahaman yang subtil) dan pada subtilitas explicandi (penjelasan yang subtil), sedangkan penelitian kesenian untuk tujuan kreatif harus mencapai subtilitas applicandi (penerapan yang subtil) dari pengetahuan tentang kesenian itu. Jelas pula bahwa dalam penerapan itu bukan hanya peneliti dari luar yang terlibat aktif, melainkan juga anggota komunitas-komunitas yang diteliti memainkan peran yang sama aktifnya. Kesenian rupa-rupanya bukan segala-galanya dan tidak merupakan suatu tujuan yang terisolasi. Praktik kesenian sekaligus menjadi sarana untuk meningkatkan saling pengertian antara peneliti dan komunitas budaya yang diteliti, yang hasil akhirnya adalah terbangunnya solidaritas yang kuat di antara kedua pihak.
Dengan lain perkataan, semua syarat-syarat yang dituntut oleh PAR telah dipenuhi dengan baik oleh Sardono dan para mahasiswanya-barangkali tanpa sekali pun membaca buku-buku teks tentang metodologi PAR sebelumnya. Eksperimen ini menimbulkan simpati, karena Sardono dan para mahasiswanya tidak sekadar menjadikan komunitas budaya yang mereka teliti sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan mereka perihal seni dan budaya-melainkan sekaligus juga mengembangkan kesadaran dan kemampuan seni budaya dari komunitas yang mereka teliti. Dengan cara yang demokratis anggota komunitas-komunitas itu dilibatkan dalam diskursus mengenai nilai-nilai budaya dan praktik-praktik kesenian mereka sendiri, sehingga mereka sendiri dengan kesadaran yang lebih baik mengembangkan potensi mereka secara optimal.
Dilihat dari perspektif perubahan budaya, hal penting yang patut dicatat ialah bahwa tiap intervensi yang dilakukan dari luar sekurang-kurangnya jangan menghilangkan rasa percaya diri dan menimbulkan rasa tak berdaya pada anggota komunitas setempat, dan sebaik-baiknya harus semakin memperkuat rasa percaya diri itu untuk menganggap bahwa apa yang mereka punyai adalah baik dan berharga, dan karena itu dapat dikembangkan dan layak dikembangkan untuk mencapai tahap realisasi yang maksimal. Kegiatan budaya apa pun hanya dapat dimulai dengan apa yang ang ada, sedangkan kepercayaan diri secara budaya ditandai oleh pandangan bahwa apa yang ada cukup berharga untuk digarap, dikerjakan kembali dalam penciptaan budaya yang terus-menerus.
BAB EMPAT
Pertanyaan yang penting dan menarik dalam hubungan ini ialah: apakah perubahan budaya itu hanya dimungkinkan karena campur tangan dari luar atau dapat terjadi karena dorongan dinamika yang ada dalam kebudayaan itu sendiri? Hal ini penting untuk melihat apakah benar bahwa ada perbedaan dan bahkan pemisahan secara kategoris antara tradisi dan modernitas. Rupa-rupanya dalam pandangan dan keyakinan Sardono tidak ada yang dinamakan tradisi, karena bahkan dalam paham-paham kesenian yang paling baku pun selalu ada usaha dan kesempatan untuk melakukan terobosan ke arah perubahan. Hal ini dapat dilakukan oleh siapa saja asal saja dia dapat memenuhi beberapa prasyarat.
Syarat pertama, seseorang harus mempunyai dan mengolah energi kreatif dalam dirinya. Bersikap kreatif terhadap kebudayaan berarti bahwa seseorang tidak saja bersedia menerima dan memanfaatkan segala apa yang ada dalam kebudayaan, tetapi juga bersedia memberikan sesuatu kepada kebudayaannya. Kebudayaan hanya akan hidup dan berkembang kalau dia tidak hanya dire-produksikan, tetapi juga diproduksikan terus-menerus. Kesenian menjadi penting karena dia dapat berfungsi sebagai semacam laboratorium, tempat nilai-nilai dan norma-norma kebudayaan diperiksa dan diuji kembali.
kebudayaan ialah dengan melihat apakah sistem pengetahuan dalam Tes yang dilakukan oleh dan melalui kesenian untuk menguji suatu kebudayaan itu masih sanggup memberikan orientasi terhadap dunia yang terus berobah. Kalau pandangan dunia dalam suatu kebudayaan sangat jauh dari keadaan dunia yang sedang dihadapi, maka kesenian akan terpanggil untuk mempertanyakan sistem pengetahuan lama tanpa menolaknya dalam keseluruhannya. Demikian pun pedoman-pedoman tingkah laku yang dirumuskan berdasarkan pandangan dunia lama akan dicoba direlatifkan atau bahkan dinegasikan secara radikal dalam eksperimen kesenian.
Syarat kedua, seorang seniman harus mempunyai kepandaian dan keberanian untuk melepaskan diri, atau sekurang-kurangnya mengambil jarak dari kekangan-kekangan dalam etos suatu kebudayaan dan mencoba memperkenalkan kemungkinan perilaku baru dalam praktik kesenian. Pembebasan diri ini jelas memerlukan suatu keberanian, karena akan berhadapan dengan pandangan dan sikap masyarakat sendiri yang masih berpegang teguh pada peraturan-peraturan menurut etos kebudayaan mereka. Sekaligus juga pembebasan diri itu perlu didukung oleh suatu ketangkasan tersendiri, karena pembaharuan yang hendak diperkenalkan melalui kesenian barulah diterima oleh anggota komunitas kebudayaan itu, kalau bentuk tingkah laku baru yang ditawarkan itu menjanjikan dan memberikan suatu kepuasan budaya yang tidak diberikan dalam etos yang lama.
Dengan lain perkataan, kreativitas estetis rupanya barulah diterima apabila disertai dengan suatu inovasi etis, yang membuat orang merasa bahwa cara-cara perilaku baru yang dianjurkan, mendorong dan memaksa mereka untuk mulai memikirkan norma-norma baru yang lebih menjanjikan perkembangan dalam rohani mereka sendiri. Pada titik itulah akan diuji apakah suatu inovasi yang dimungkinkan oleh kreativitas estetis bersifat otentik atau tidak otentik.
Cerita Sardono mengenai dua guru tari di Solo menjadi ilustrasi yang sangat indah tentang pentingnya etos dan perlunya pembaharuan dalam etos suatu kebudayaan. Kedua guru tari tersebut adalah R. Ng. Atmokesowo dan R.Ng. Wignyo Hambekso. Atmokesowo adalah seorang yang memenuhi ideal seorang penari keraton. Tinggal dalam lingkungan keraton, hidup dan penampilannya sehari-hari selalu rapi dan terkendali. Menghindari minuman keras, dia gemar duduk merenung seakan tenggelam dalam meditasi Vipasana. Bertubuh kecil dan halus, bertutur kata lembut, dia berada jauh dari keramaian yang tak perlu dan menghindari kegembiraan yang berlebihan. Dia menjadi personifikasi dari tarian halus keraton, juga dalam hidupnya sehari-hari. Sementara R. Ng. Wignyo Hambekso tampil dengan perilaku dan kebiasaan yang amat berlainan. Dia dikenal sebagai tokoh urakan, dengan temperamen yang meledak-ledak dan tidak tertib secara sosial. Akan tetapi dia dikagumi sebagai guru tari yang mempunyai perbendaharaan tari yang seakan tak ada habis-habisnya. Yang unik padanya ialah bahwa gerak-gerak tari yang baru itu biasanya ditemukannya dalam keadaan mabuk atau setengah mabuk setelah dia menenggak minuman keras. Orang-orang di kota Solo lalu menganggap dan menyebarluaskan cerita bahwa guru tari ini seakan mempunyai sebuah gudang antik yang berisi berbagai gerak tari yang hanya dapat dibuka olehnya sendiri pada waktu-waktu tertentu, khususnya kalau dia sedang dalam keadaan mabuk atau setengah mabuk. Dalam bahasa ilmu antropologi sekarang maka guru tari ini seakan melakukan reinvention of culture yaitu menemukan kembali kebudayaan. Jadi, pola-pola, kebiasaan-kebiasaan dalam suatu kebudayaan yang sudah mulai dilupakan ditemukannya kembali.
Dalam pandangan Sardono yang mengenal kedua guru tari tersebut, anggapan ini tidaklah benar. Apa yang terjadi bukanlah terbukanya sebuah gudang antik yang penuh dengan gerak-gerak tari yang belum dikenal, melainkan penciptaan biasa, ketika seorang seniman mengerahkan kreativitasnya. Yang dilakukan guru tari Wignyo Hambekso tak lain dari menciptakan gerak-gerak tari baru yang diminta orang. Kebiasaannya untuk menciptakan gerak-gerak tari itu dalam keadaan mabuk mudah pula dijelaskan, karena setelah menenggak minuman keras dan menjadi mabuk, dia terbebas dari pakem-pakem seni tari yang sudah baku, dan terbebas juga dari kekangan-kekangan dalam kebudayaan sehingga dapat leluasa menciptakan gerak-gerak yang baru.
Tidak ada gudang antik yang dibuka secara berkala. Yang ada hanyalah tenaga kreatif yang dibebaskan untuk mencipta dengan leluasa dalam kemerdekaan yang tak terkekang. Ini artinya pembaharuan dalam suatu kebudayaan dapat juga terjadi kalau tidak ada intervensi dari luar, asal saja orang-orang yang hidup dalam kebudayaan tersebut dapat mendayagunakan potensi kreatifnya setelah potensi-potensi tersebut dibebaskan dari kungkungan inhibisi yang juga terdapat dalam kebudayaan bersangkutan.
Syarat ketiga, seorang seniman hendaknya sanggup mengubah kesulitan menjadi momentum dan mengelola kesempitan menjadi kesempatan. Dalam hal Sardono, kedatangannya ke Nancy, Perancis, atas namanya sendiri dan bukannya atas nama suatu misi kesenian, tidaklah terbayangkan, seandainya sebelumnya dia tak mengalami kekecewaan yang amat pahit, tatkala rencana pertunjukan tari kecak di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, bersama delapan puluh penari Desa Teges, Bali, batal gara-gara tak diizinkan oleh Listibya (semacam supervisor kesenian di Bali) di Denpasar. Pembatalan itu terjadi demikian mendadak menjelang keberangkatan dengan dua bis ke Jakarta, yang untuk beberapa anggota rombongan merupakan perjalanan pertama ke luar Bali. Di tengah persiapan terakhir Sardono dipanggil ke Denpasar hanya untuk menerima surat pembatalan dan pelarangan oleh Listibya.
Seluruh desa menangis dan bertanya berhari-hari apa gerangan salah mereka sehingga mendatangkan kutuk dewa yang menyambar bagai petir di siang hari bolong. Sardono terpukul. Dia ingin menuntut secara hukum dengan bantuan LBH. Tetapi renungan berikutnya membuat dia terpaksa mengurungkan niatnya. Dia paham bahwa seandainya pun dia memenangkan perkara itu di pengadilan, kemenangan itu hanya formal belaka, yang tak akan menguntungkan rekan-rekan penarinya di desa Teges. Hal yang sebaliknya sangat mungkin terjadi, yaitu bahwa penduduk Desa Teges akan mengalami tekanan yang lebih banyak dan semakin berat dari para pejabat kebudayaan di Denpasar. Frustrasi Sardono meningkat, jiwanya rusuh. Dia merasa harus meninggalkan Indonesia untuk menemukan ketenangan batin dan memulihkan keseimbangan jiwa.
Dalam kemelut itu dia ingat akan sepucuk surat lama yang pernah mengundangnya datang ke Perancis. Maka dengan tekad bulat, disertai modal sekadarnya, dia bersama penari Sentot memutuskan datang ke Nancy, sebagai penari yang belum dikenal dalam pergaulan seniman-seniman dunia. Tiba di Nancy semua acara telah tersusun, sehingga Sardono dan Sentot hanya diperbolehkan menari setelah acara utama selesai menjelang tengah malam. Akan tetapi frustrasi di tanah air, perasaan tak berdaya di negeri orang, rupanya telah melecut kemampuan dan tenaga dua penari itu, yang dalam beberapa malam meledakkan reputasi mereka.
Nancy seakan mendapat pujaan baru yang datang dari suatu tempat nun jauh di Timur. Setelah gebrakan pertama yang menggemparkan, sukses berikut sebagai pengajar tari yang mendapat tawaran bertubi-tubi merupakan akibat yang hampir logis saja. Teges telah mendorong Sardono ke Paris untuk membalas kekalahannya di tanah air dengan kemenangan yang meyakinkan di mancanegara.
Dilihat sepintas lalu sukses Sardono seakan diakibatkan oleh kesanggupannya memanfaatkan momentum. Namun harus segera ditambahkan bahwa momentum itu buat sebagian telah diciptakannya sendiri, dengan mengubah energi yang lahir dari frustrasi yang pahit menjadi dendam yang membara dengan tenaga yang membuatnya tampil tuntas, total, dan menggetarkan.
Kreativitas bukan saja berhubungan dengan kemampuan menciptakan suatu karya seni, tetapi juga berhubung dengan pengelolaan tenaga untuk suatu tujuan yang ditetapkan dengan hati yang bulat, dan sekaligus penciptaan kesempatan dan prasyarat di mana daya cipta bisa diwujudkan, meskipun terdapat berbagai kendala. Pada titik itu terlihat bahwa meminta syarat-syarat kebebasan untuk tumbuhnya kreativitas merupakan tuntutan yang hanya dapat dibenarkan separuhnya, karena syarat-syarat objektif berupa kebebasan dan fasilitas tidak dengan sendirinya akan melahirkan karya yang subur. Sebaliknya, halangan-halangan objektif yang ada dapat menjadi sebab yang menantang kreativitas seseorang untuk mengubah halangan menjadi tantangan yang merangsang kreativitas, yang dalam keadaan tenang dan normal mungkin tidak cukup terangsang untuk muncul dan berkembang.
BAB LIMA
Sardono menulis dengan menggunakan memori dan asosiasi-asosiasi yang kuat. Membaca tulisannya ibarat menghadapi panorama yang sangat kaya. Gagasannya digerakkan oleh intuisi demi intuisi, dan sebagai pembaca kita harus aktif dan lincah bergerak mengikuti loncatan-loncatan pemikirannya, dalam irama yang tidak selalu teratur. Tulisan-tulisan ini adalah contoh soal tentang bagaimana pikiran pun dapat menari-nari mengikuti bunyi gendang atau terpancing oleh rangsangan dari sekitar.
Sebagaimana “jalan pikiran” diukur berdasarkan ketepatan dan arah langkah-langkah, maka demikian pun pemikiran yang menari-nari hanya dapat diukur berdasarkan kelenturan gerak yang tepat menanggapi bunyi musik. Dengan demikian, manfaat esai-esai ini tidaklah terletak pada proposisi-proposisi yang dapat diuji tentang kebudayaan, melainkan pada kemampuannya merangsang pemikiran orang lain, seperti halnya gerak seorang penari memancing respons penari lainnya. Tidak ada pretensi atau klaim tentang validitas pengamatan-pengamatan yang dikemukakan. Yang tampil adalah pentasan buah pikiran yang ditawarkan kepada suatu khalayak, yang kemudian dipersilahkan menyenangi atau menolaknya, mengambil atau membuangnya.
Dikatakan secara teknis: esai-esai ini selayaknya diapresiasi dalam context of discovery dalam dunia ilmu pengetahuan, sebagai pembuka jalan bagi orang lainnya untuk menemukan sendiri apa yang dicarinya. Dalam tradisi epistemologi metode ini lebih dikenal sebagai heuristika, yang mengingatkan orang akan riwayat Archimedes di masa Yunani kuno, yang menemukan apa yang kemudian dikenal sebagai hukum Archimedes dalam ilmu fisika, ketika dia berlari keluar dari air dalam keadaan telanjang bulat untuk menyatakan “Eureka!” yang berarti “Saya sudah menemukan”. Pada sisi lain pemikiran-pemikiran Sardono harus berhadapan dengan risiko, kalau diuji dalam suatu context of justification, berupa tuntutan-tuntutan metodologis yang akan memeriksa apakan gagasan yang diajukannya mempunyai validitas tertentu, dan apakah persepsi-perspesi kebudayaannya dapat diterjemahkan menjadi langkah-langkah operasional dalam penelitian dan kajian empiris.
Bagaimanapun soalnya, di sini kita dapat melihat beberapa contoh, bahwa simpati dan perhatian yang sungguh-sungguh dari seorang pengamat dan peneliti, dapat membawanya kepada beberapa apresiasi kualitatif, yang sekali pun belum teruji validitasnya secara metodologis, dapat bermanfaat memberikan ilham kepada orang lain untuk merencanakan kajian dengan hasil-hasil yang dapat diuji kesahihannya. Sebuah tarian pada akhirnya tidak dapat dihadapi dengan tuntutan terhadap validitas. Dia hanya dapat diukur dari kesanggupannya membuat Anda turut menggoyangkan tubuh atau malahan meninggalkan tempat itu dengan rasa jenuh.
Jakarta, 6 Mei 2003

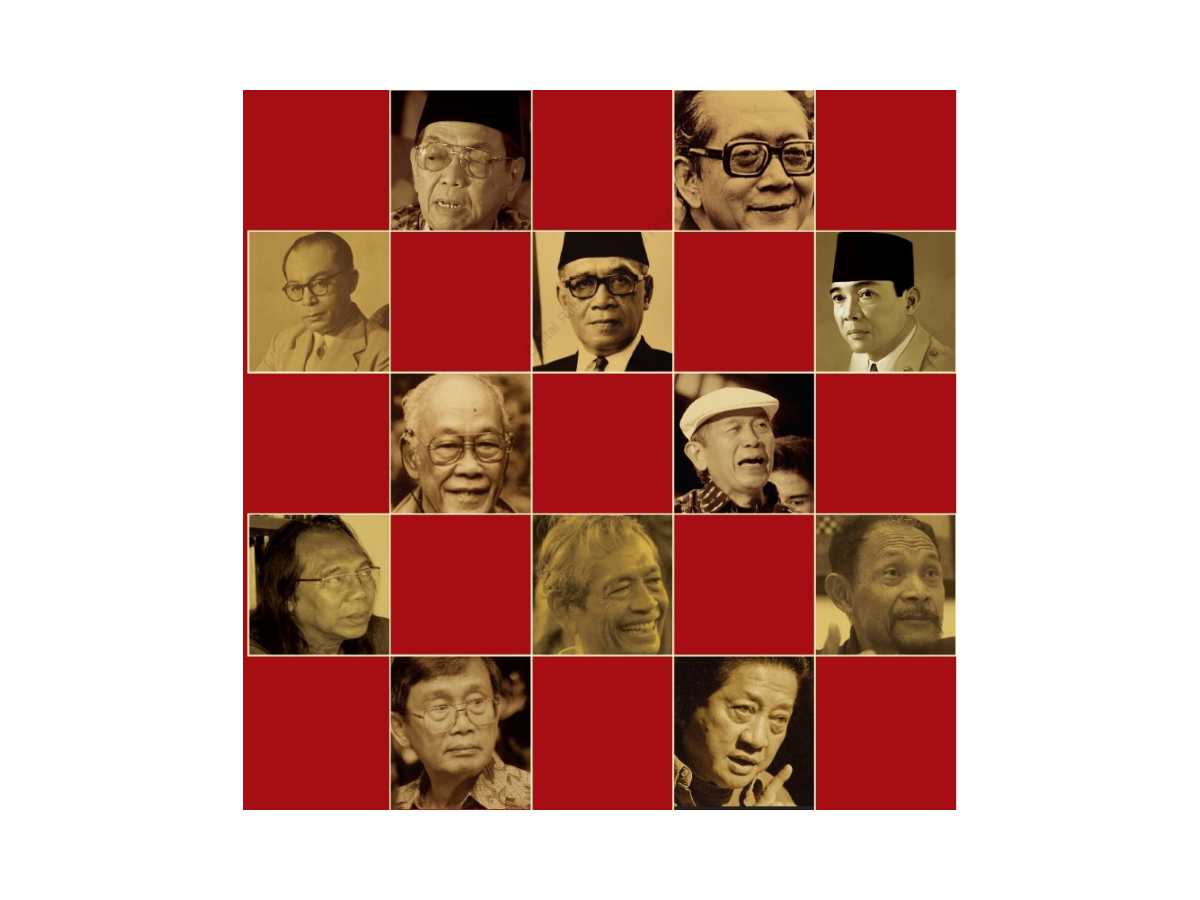
Leave a Reply